Seperti bayi yang kehilangan dotnya, aku mencari ke setiap sudut rumah. Aku tidak bisa dan tidak biasa berteriak seperti tuan besar. Matahari yang sudah tinggi dan penat membuatku terduduk di lantai usai melongok kolong meja untuk kesekian kalinya.
Sepasang kaki indah menyembul tepat di hadapanku. Kaki yang sangat kukenal milik perempuan cantik, ratu yang menghuni hatiku sekian lama. Untuk mendapatkannya, aku rela meninggalkan semua milikku di masa lalu. Bahkan, imanku pun turut kugadaikan agar aku dapat memilikinya.
Tiada kuhirau tangis ibuku atau runtuk ayahku, apalagi ceramah adikku. Aku melenggang gembira menyambut hari baruku bersamanya.
Sepuluh tahun telah berlalu, segala kemewahan dunia telah kupunya, sedang hubunganku dengan keluarga ya begitulah. Apa mau dikata, aku tidak bisa memilih cinta yang menjeratku di persimpangan antara baktiku pada Ayah-Ibu dan sayangku pada keluargaku yang baru.
Sebagai sulung, aku adalah harapan keluarga pada awalnya. Tapi ingkarku membuatku turun takhta. Aku dicoret dari daftar keluarga. Tak ada lagi yang mengikatku dengan mereka katanya.
Aku menerima ini sebagai konsekuensi dari pilihan hidup yang aku jalani. Sungguh tak sekalipun aku melupakan kewajibanku sebagai anak kepada orang tua, tapi ayahku selalu menerimanya dengan dingin.
Bukan materi yang mereka harap, tapi kembalinya buah hati, demikian mereka berkata seraya memelukku dengan linangan air mata yang tak pernah kering setiap kali aku menemui mereka.
Sudah dua lebaran aku tidak pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarga, mereka pasti maklum dan aku tahu mereka tidak begitu mengharapkan kedatanganku. Ada atau tidak ada aku tidak ada bedanya.
Sungguh ini bukan disengaja, mangkirku, karena ada acara di rumah mertua yang berdekatan dengan hari raya, tapi mereka pasti berpikiran lain. Aku datang di waktu lain dan hanya bertemu Ayah-Ibu, yang lain tidak mungkin karena libur rayaku lain.
Sebenarnya jauh di lubuk hati, ada kerinduan yang menggelayut, mengganggu langkahku. Tak bisa kupungkiri bahwa meskipun ada lagu lain yang kini mengalun memenuhi telinga dan mengiringi setiap langkahku, tetap saja terbersit alunan tilawah yang sering melagu di setiap senja di langgar dekat rumah dulu.
Kesibukan yang bertumpuk dan perhatian serta cinta tak terkira dari istriku menghapus begitu saja bayangan yang menganggu. Kembali langkahku menatap ke depan tanpa sempat memikirkan yang telah lalu.
Aku percaya inilah jalan yang Tuhan pilihkan untukku. Aku menerimanya dengan ringan. Orang-orang baru di sekelilingku menyambutku dengan sukacita, tapi orang-orang di masa lalu selalu mengangguku dengan tangis yang tak kunjung usai juga.
*****
Kaki indah di depanku bergeming, kaki yang membuatku rela berlutut dan meninggalkan sujud. Aku mendongak mengharap senyum kutemukan di bibirnya yang indah, senyum yang membuatku takluk pada setiap kata yang terucap. Tapi ternyata aku salah.
Matanya yang sejuk bening seperti telaga yang mampu menghanyutkan aku hingga ke seberang melotot penuh dendam. Tangannya berkacak pada pinggangnya yang ramping terawat seiring usia yang terus merambat.
Aku mengulurkan tangan berharap manja pada jemarinya, tapi lemparan koran yang aku terima tepat di mukaku yang menatapnya dengan sejuta tanya. Kuraup koran yang berserakan memenuhi badan. Aku tidak menemukan apa yang membuatnya seperti kesambet setan.
Bukan berlagak bodoh kalau tampangku jadi dongo, aku sedang mencari artikel apa kiranya yang menarik perhatiannya hingga rela bangun pagi tidak seperti biasanya,
Masih dengan wajah kesambet, istriku menunjuk lembar halaman sastra, di situ tertera nama yang membuatku terlempar ke masa silam. Aku kini paham dan hanya bisa terdiam, tidak ada kesempatan bagiku untuk menjelaskannya sekarang.
Aku menurut saja seperti kerbau tercucuk hidungnya sewaktu istriku menyorongkan deretan bait sajak yang tercetak.
Smoga
kiranya airmata
tahajudku kembalikan
hatimu padaNya
seribu bulan ku akan
menunggu dalam doa.
Aku mengernyitkan dahi. Sepertinya aku pernah membacanya, tapi di mana? Istriku melempar hp ke pangkuanku.
“Tersanjung?” istriku mencibir. Aku juga melakukan hal yang sama waktu pertama menemukan sms yang bunyinya tidak jauh beda.
Aku membalasnya dengan mengatakan, “Jangan melakukan hal yang sia-sia.”
Tak surut pantang menyerah, selalu saja ada pesan masuk ke hpku bangunkan pagiku dan aku terus menggerutu. Pernah sebulan aku terbebas dari pesan yang mengguru itu, tapi aneh, bukan tenang yang kudapat.
Aku kelimpungan seperti kehilangan cahaya pagi, tentu saja tak kutunjukkan muka gelisah di depan isriku. Bisa runyam perkara kalau ia curiga.
Sekarang apa yang harus kukatakan kalau ternyata ia melanggar kesepakatan tentang hak pribadi, termasuk hp pribadi? Aku tak pernah mengusik barangnya tanpa seizinnya. Kini ia melempar hpku untuk menunjukan bahwa ialah yang berkuasa atas diriku di rumah, juga di setiap gerakku?
Tidak ada yang harus kusembunyikan darinya. Semua masa lalu telah kukubur bersama ikrar yang kubangun atas nama cinta. Semua surat yang keluar-masuk dan hp aku taruh di tempatnya tanpa kukunci. Silakan saja. Jadi kalau ia membaca pesan yang seharusnya untukku, salah siapa?
Gerah juga menjadi tertuduh tanpa hak membela. Kusingkirkan koran tanpa melanjutkan baris berikutnya, aku sudah hafal semua di luar kepala. Sekadar hafal, tahu maknanya, tapi tidak tergerak untuk memahami yang tersirat di balik setiap kata.
Aku melangkah ke kamar mandi untuk berendam, menyegarkan otakku yang buntu, mencari alasan yang jitu agar terhindar dari perang yang sudah dikibarkan istriku.
Kuselonjorkan kakiku di washtub dan mencoba memejamkan mata mencari kata-kata. Dalam keadaan lelah hati dan lelah raga seperti ini, aku tak tahu apa yang ada dalam benakku. Sayu mataku mengantarku pada masa lalu.
Aku berlari mengejar panggilan adzan bersama teman-teman. Aku tersipu waktu tak sengaja bersenggolan di sudut langgar usai mengambil wudu.
“Batal!” teriak temanku dan aku menurut disuruh mengulang wudu. Gadis kecil itu juga.
Ternyata dia anak baru. Mulai hari itu, dia ada di dalam hatiku hingga datang waktu memisahkan kami. Aku harus ke kota melanjutkan kuliah hingga mendapat pekerjaan yang ternyata menjadi jurang yang memisahkanku dengan masa lalu.
Aku masih ingat waktu ia mengeja Al Ikhlas dan tarjamahnya di depan kelas sementara aku kebagian membaca Al Kafirun. Aku menghafal sambil melihat mulutnya yang ikut komat kamit menolongku yang terbata-bata. Lega akhinya aku hafal juga.
“Alhamdulillah. Jangan sekedar dihafal ya, Nak, tapi diamalkan juga,” begitu Bu Guru berpesan pada kami semua.
Suara lembut Bu Guru membangunkanku. Bergegas aku mengambil wudu setelah menutup auratku. Aku mengejar suara adzan yang bergema dari masjid di ujung jalan. Istriku mengejar sampai ngos-ngosan, matahari membakar kulitnya yang selembut salju.
“Mas mau ke mana?”
“Pulang!” jawabku mantap.
“Rumah kita di sana,” katanya menunjuk ke belakang.
Tidak! Aku tidak mau menengok ke belakang. Aku tidak mau pulang ke rumah yang telah menyilaukan dan membutakan mata hatiku.
“Mas!” istriku menarik tanganku.
“Batal!” teriakku. Aku tak mau terjamah tangannya yang tak kenal air wudu.
Aku terus berlari dan istriku terus berteriak. Aku tidak mau menoleh lagi. Takkan pernah kusesali meski yang kubawa hanya kain yang menempel di badan.
Aku menatap lurus jalan di depan yang membentang mengantarku pulang, pulang ke rumahNya yang Maha Kaya lagi Maha Penyantun, yang Maha Penyayang lagi Maha penerima tobat sebelum hari menjadi gelap…
******
PM 2:38 ’020807


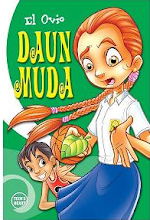
0 komentar:
Posting Komentar